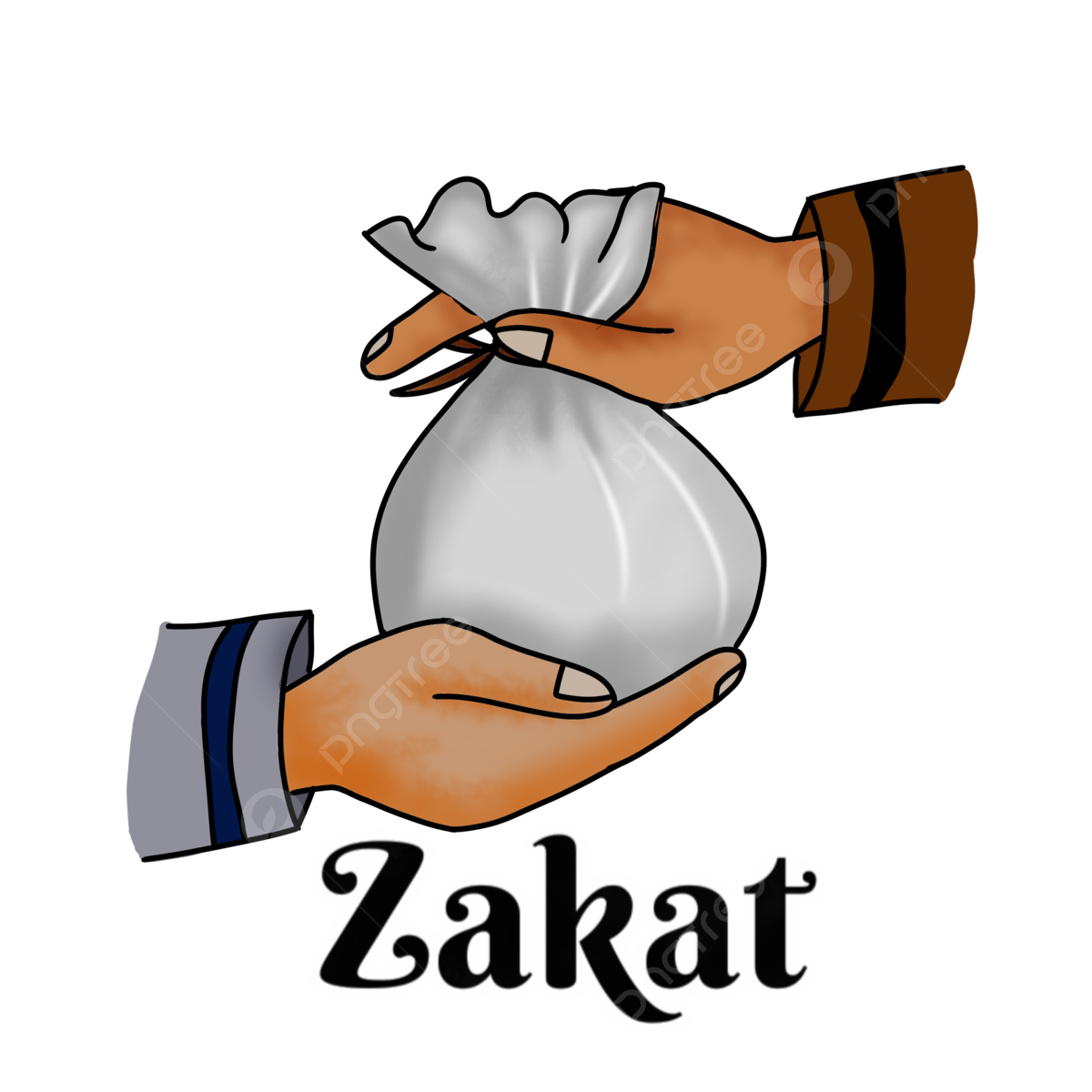Golongan (ashnaf) orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur`an secara tegas dengan menggunakan innamâ sebagai pembatas. Artinya, zakat tidak boleh disalurkan diluar ashnaf yang disebutkan dalam Al-Qur`an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٦٠
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah [9]: 60)
Fakir dan Miskin
Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi fakir dan miskin, siapa yang lebih membutuhkan diantara mereka dan bagaimana konsekwensi hukumnya. Secara ringkas, menurut madzhab Syafi’i dan Hanbali, fakir lebih parah tingkat kebutuhannya daripada miskin. Karena fakir menurut mereka adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Sementara miskin adalah orang yang mampu bekerja akan tetapi penghaslannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
Sementara menurut Maliki dan Hanafi miskin justeru lebih membutuhkan daripada fakir, seperti dalam surah al-bayyinah, “atau orang miskin yang berdebu” yang menunjukkan keparahan tingkat kesulitan hidup. Miskin bagi mereka adalah orang yang tinggal dimanapun mereka berada, karena mereka tidak memiliki rumah untuk singgah.[2]
Menurut hemat penulis, jika salah satu disebutkan secara terpisah, maka maknanya mencakup keduanya, karena diantara keduanya disatukan oleh sifat musytarak, yaitu membutuhkan. Akan tetapi jika keduanya disebutkan secara beriringan maka ada sedikit perbedaan makna.
Dalam kondisi ini, fakir, lebih membutuhkan daripada miskin. Pertama, karena kelompok fakir disebutkan terlebih dahulu daripada miskin. Kedua, sesuai dengan pengertian lughawinya, bahwa al-faqr berarti tulang belakang. Ketiga, sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Kahf, “adapun perahu itu adalah milik seorang miskin..” artinya, kelompok miskin meskipun membutuhkan, akan tetapi sedikitknya ia memilik kasab untuk menopang hidupnya, hanya saja hasil kasabnya tidak mencukupi.
Petugas Zakat (Amilin)
Amilin merupakan bentuk jamak dari ‘amil, artinya yang berbuat, bekerja. Dalam istilah syara, amil adalah orang yang ditunjuk pemerintah untuk memungut, mengelola dan menyalurkan zakat.
Menurut Ibnu Qudamah[3], amil adalah kelompok ketiga yang berhak memperoleh bagian zakat. Mereka adalah petugas yang diutus imam untuk mengambil zakat dari para pemilik harta, mengumpulkan, menjaga dan menyalurkannya, dan (termasuk amil) orang-orang yang membantunya, seperti sopir, penggembala, demikian pula akuntan, pencatat, penakar, dan orang-orang yang diperlkukan dalam mengurus zakat.
Adapun kadar yang diberikan untuk amil bervariasi. Amil tidak tetap diberikan bagian sesuai dengan pekerjaannya. Jika ia seorang amil tetap dan dalam keadaan fakir, maka ia diberikan zakat yang mencukupi kebutuhannya, sementara jika ia seorang yang kaya maka diberlakukan sistem upah. Akan tetapi, bagian amil hendaknya tidak lebih dari 1/8 dana zakat.
Yang dibujuk hatinya (Muallaf)
Secara etimologi, al-muallafah qulûbuhum berasal dari dua kata; muallaf dan qulûb. Muallaf adalah isim maf'ul dari kata 'ulfah', yang berarti bersatu, berkumpul dan bersinergi. Dalam Tâj al-'urûsy disebutkan "allafa bainahumâ", berarti menanamkan rasa kasih sayang dan menyatukan mereka setelah bercerai berai.[4] Sedangkan qulûb adalah bentuk jamak dari kata qalb, yang berarti hati. Al-Zubaidi mengutip pendapat Ibnu Hisyam, "al-qalb mempunyai empat arti, yaitu hati, akal, ringkasan dan inti segala sesuatu."[5]
Menurut Ulama Hanafiah, muallaf adalah para pembesar bangsa Arab, seperti Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn dan Aqra' bin Habis. Rasulullah saw memberi mereka bagian zakat untuk melunakkan hati mereka terhadap Islam. Dikatakan pula: mereka sudah ememluk Islam, dikatakan pula: mereka berjanji untuk memluk Islam.[6]
Menurut ulama Malikiyyah, muallaf adalah orang kafir yang diberikan bagian agar memluk Islam.[7] Demikian dalam al-Mudawwanah al-Kubrâ disebutkan, "dan Imam Malik berkata: dan tidak diberikan dana zakat kepada orang majusi, yahudi, nashrani dan budak."[8]
Sementara madzhab Syafi'i berpendapat bahwa muallaf adalah mereka yang memeluk Islam akan tetapi masih lemah keislamannya, atau, seorang yang kuat keislamanyya, akan tetapi ia memloiki posisi yang sangat terhormat, maka ia diberikan bagian zakat dengan harapan bisa mengislamkan yang lainnya.[9]
Dan dalam pandangan madzhab Hanbali, muallaf adalah tokoh yang ditaati kaumnya, dari golongan yang bisa diharapkan keislamannya, atau dikhawatirkan keburukannya, atau diharapkan akan menguat keimanannya setelah diberikan zakat, atau membawa rekannya memluk islam, atau menarik zakat dari orang yang enggan membayarnya atau untuk mencegah keburukan bagi kaum muslimin.[11]
Ibnu Muflih berkata, "Mereka adalah para pembesar yang ditaati pengikut-pengikutnya yang diharapkan keislamannya, atau ditakutkan keburukannya, atau untuk menguatkan keimanannya atau membuat orang yang sepadan dengannya masuk Islam.[12]
Dari berbagai pandangan para ulama, maka bisa disimpulkan bahwa muallaf tidak harus selalu orang yang baru memeluk Islam, akan tetapi, setiap orang yang dibujuk hatinya, baik itu pembesar kaum muslimin yang memegang jabatan strategis, kaum muslimin yang tengah berperang dengan kristenisasi bahkan kaum kafir yang diharapkan kebaikannya demi umat Islam.
Adapun kadar zakat yang diberikan kepada mereka ditentukan oleh kebijakan pemerintah, dalam hal ini amil zakat.
Hamba Sahaya (ar-riqâb)
Ada dua pendapat mengenai riqâb yang dimaksud dalam surah at-Taubah: 60. Pertama, hamba yang sedang berupaya menebus dirinya (al-mukâtab). Kedua, orang yang memerdekakan hamba sahaya dengan harta zakat. Inilah isi surat yang ditulis az-Zuhri kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz.[18]
Persoalannya, pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, lalu, apakah bagian ini kemudian terputus dan tidak difungsikan? Berdasarkan tujuan diberikannya bagian riqâb adalah untuk melepaskan kaum muslimin dari kehinaan dan belenggu yang mengikat kemerdekaannya, karena itu, boleh diberikan untuk menebus tawanan kaum muslimin, membantu perjuangan bangsa muslim untuk merebut kemerdekaan, bahkan untuk menebus muslim yang diculik sesuai dengan kebijakan yang berwenang (amil).
Gharimin (yang berutang)
Al-gharm secara bahasa berarti al-luzûm (kekal). Dalam istilah gharim adalah orang yang berutang baik bagi dirinya sendiri maupun untuk pihak lain. Dalam prakteknya gharim terbagi dua: berutang untuk kepentingan orang lain dan berutang untuk kepentingan pribadi.
Gharimin untuk kemaslahatan orang lain diberikan hak zakat meskipun ia termasuk orang kaya. Rasulullah saw bersabda, “tidak halal meminta-minta bagi orang yang kaya kecuali lima kelompok. Lalu Rasulullah saw menyebutkan gharimin sebagai salah satunya.[19] Kemudian karena ia berutang untuk kemaslahatan ummat, maka, posisinya sama dengan fi sabilillah, amilin dan muallaf.
Sementara gharim yang berutang untuk keperluan pribadiKelompok ini tidak diperboilehkan mendapatkan bagaian zakat kecuali ia tidak sanggup membayar dengan hartanya sendiri. Dengan demikian, ia termasuk kedalam kelompok fakir miskin.
Akan tetapi, ada syarat-syarat tertentu yang membuat gharim berhak mendapatkan zakat:
- 1. Tidak berutang dalam kemaksiatan
- 2. Orang yang berutang masih hidup.
- 3. Tidak sengaja berutang agar mendapatkan bagian zakat dengan cara berbelanja secara berlebihan.
Di Jalan Allah (Fî Sabîlillâh)
Yang dimaksud sabilullah adalah berjuang di jalan Allah. Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran fi sabilillah. Secara garis besar ada tiga pendapat dalam hal ini:
Pertama, tentara yang berperang di jalan Allah dan tidak memiliki gaji tetap dari diwan. Ini adalah pendapat Jumhur Ulama dari Malikiyyah, Syafi’iyyah, Hanabilah dan sebagian Hanafiyah.
Kedua, semua bentuk ketaatan kepada Allah. ini adalah pendapat Hanafiyah, dan mayoritas ulama kontemporer.
Ketiga, jihad dengan maknanya yang umum, mencakup perang dengan pedang, dengan pena dan dengan lisan. Ini adalah keputusan Majma Fiqih.[20] Pendapat ini lebih tepat, karena pada zaman sekarang peperangan tidak lagi mengambil bentuk pertempuran fisik, akan tetapi peperangan ekonomi, budaya dan pemikiran. Bahkan, efek yang ditimbulkan peperangan ini jauh lebih hebat. Peperangan fisik, meskipun sangat berat, akan tetapi akan memperkuat barisan kaum muslimin dan menetapkan kaki mereka diatas agama, sementara peperangan non fisik, justru akan menggiring ummat sedikit demi sedikit untuk menjauhi agama.
Sehingga, para da'i dan pencari ilmu agama yang menghabiskan waktunya untuk berjihad dengan ilmunya berhak mendapatkan bagian zakat dari kelompok fi sabilillah. SyeikhSyaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya : Apakah hukumnya memberikan zakat kepada para penuntut ilmu (pelajar)? beliau menjawab, "Penuntut ilmu yang mencurahkan kemampuan dan meluangkan waktunya untuk mencari ilmu syari’at meski dia mampu berusaha (mencari nafkah) tetap boleh diberi zakat, karena menuntut ilmu termasuk salah satu macam jihad fi sabilillah."
Ibnu Sabil
Ibnu sabil adalah kiasan bagi musafir atau orang yang tengah berada dalam perjalanan. Dalam kmonteks zakat, para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian ibnu Sabil.
Menurut Ibnu Qudamah ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan dan tidak memiliki bekal untuk kembali ke negrinya.[21]
Al-Kasani dari Hanafiyah[22] dan al-Qurafi dari Malikiyah[23] mendefinsiikannya sebagai orang asing yang tidak mampu mengakses kekayaannya, meskipun di negrinya ia termasuk orang kaya.
Sementara Syafi’iyyah mendefinisikannya sebagai orang yang dalam perjalanan atau hendak bepergian dari suatu negri, baik negri asalnya atau bukan.[24]
Definisi ini berbeda dengan yang lainnya karena mencantumkan orang yang hendak bepergian sebagai kategori Ibnu Sabil.
Sebagaimana gharim, Ibnu Sabil juga harus memenuhi beberapa syarat, sehingga ia dikatgorikan berhak menerima zakat:
- 1. Bepergian bukan dalam rangka maksiat
- 2. Harus benar-benar di tengah perjalanan
- 3. Benar-benar membutuhkan.
Adapun kadar yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhannya, sehingga ia dapat sampai ke negri asalnya, termasuk biaya akomodasi jika ia menginap tidak lebih dari tiga hari, karena, selama waktu itu ia masih dianggap sebagai ibnu sabil.
Daftar Rujukan
[1] Quraisy Shihab, Wawasan Al-Qur`an, Bandung: Mizan, 2006, hlm. 442
[2] Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh, 870
[3] Syamsuddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi, asy-Syarh al-Kabîr, Giza: Hijr 1993, 7/222, lihat juga Hukum Zakat, hlm. 545.
[4] Sayyid Muhammad Murtadha al-Husaini al-Zubaidi, Tâj al-Urûsy fi Jawâhir al-Qâmûs, Kuwait: Wuzârah al-I'lâm, 1986, Jilid 23/33
[5] Tâj al-Urûsy, Jilid 4/70
[6] al-Ghafily, Nawâzil al-Zakât; hlm. 390
[7] al-Ghafily, Nawâzil al-Zakât, hlm. 390
[8] Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi, Al-Mudawwanah al-Kubrâ, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, Jilid 1/346
[9] Syamsuddin Muhammad bin Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtâj,Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997, 3/144
[10] Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm, Mekah: Maktabah al-Asadi, 2003, Cet. V, Jilid 3/418
[11] Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni 'ala Mukhtashar al-Khiraqi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, Juz 2/697
[12] Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Muflih, al-Mubdi' fi Syarh al-Muqanna', Damaskus: al-Maktab al-islamy, 1973, juz 2/430
[13] 'Alauddin al-Kassany, Badaa`i' al-Shanaa`i', Darul Kutub al-Araby, 1982, Jilid 2/45
[14] Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh, Jilid 2/872
[15] Ibnu Qudamah, al-Mughni, Jilid 4/125
[16] Asy-Syaukani, Nail al-Authâr, Jilid 4/234
[17] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, Pedoman Zakat, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, Edisi II, 2006, hlm.
[18] Hukum Zakat, hlm. 589
[19] HR. Abu Daud 1637
[20] Ali Salus, Mausû’ah Qadhâyâ fiqhiyyah Mu’âshirah, Beirut: Muassasah Rayyan, 2002, hlm. 565
[21] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 2/1579
[22] Badaa’i, 2/74
[23] Al-Qurafi, adz-Dzakhîrah 3/148
[24] Muhyiddin bin Syarf Al-Nawawi, Al-Majmû’, Jeddah: Maktabah Irsyad, tt, 6/203